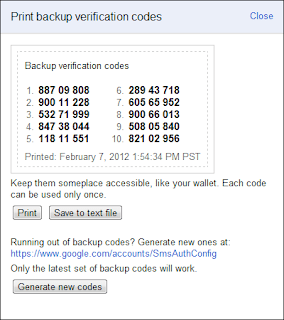Kisah Mantan Perempuan ISIS
Sophie Kasiki memandang nanar sebuah rekaman bocah berbahasa Inggris memakai seragam tentara dan bandannya hitam bertuliskan huruf Arab. Si anak berseru, mereka yang 'kafir' pantas untuk dibunuh. Kata-katanya adalah bagian dari propaganda militan garis keras.
Air mata Sophie membasahi pipinya. Ia berkali-kali menelan ludah.
"Anak itu bisa saja anakku," ujarnya pelan kepada The Guardian. Sophie adalah perempuan yang terpikat janji surga ISIS.
"Aku sungguh tak bisa berbicara apa-apa. Rekaman itu membuatku menangis. Sungguh, aku dan anakku lebih baik mati daripada menjadikannya ia pembunuh, daripada membiarkannya jatuh ke cengkraman monster itu," isaknya.
Monster yang ia maksud adalah ISIS. Kini suara Sophie lebih lantang. Ia berkisah bagaimana ia nyaris membuat anak lelakinya yang masih berusia 4 tahun jadi pembunuh hanya karena ia menyerahkan dirinya ke kelompok itu.
Sophie adalah satu dari sekian ratus perempuan Barat yang nekat ke Raqqa. Kota itu disebut-sebut sebagai pusat pemerintahan ISIS di Suriah. Ia juga salah satu dari sedikit perempuan yang selamat kembali ke negaranya. Sophie mengkisahkan pengalamannya itu adalah perjalanan ke neraka.
"Aku sungguh merasa bersalah. Berkali-kali aku berkata kepada diriku, bagaimana aku bisa hidup dengan apa yang telah aku lakukan, yaitu membawa anakku ke Suriah," kisahnya kepada the Observer.
"Aku benci dengan mereka yang telah memanipulasiku, mereka yang berhasil mengeksploitasi kenaifanku, kelemahanku, serta ketidakamananku. Aku benci diriku sendiri," ujarnya lagi.
Lebih dari 220 perempuan Prancis dipercaya berada bersama ISIS di Irak dan Suriah, menurut dinas intelejen. Dua tahun lalu, hanya 10 persen yang pergi meninggalkan negara itu untuk menjadi bagian ISIS.
Namun, kini lebih dari 35 persen dari mereka pergi ke Suriah bergabung bersama ISIS dan hanya sedikit yang berhasil pulang dan selamat seperti Sophie. Kisahnya dibukukan dengan judul Dans La Nuit de Daech (Malam-malam Bersama ISIS).
Sophie, perempuan mungil berusia 34 tahun. Namun ia sungguh tangguh, kendati ia tak menyangka dengan mudahnya terekrut ole ISIS. Ia tak ingin memberikan nama aslinya, takut balas dendam kelompok teroris itu.
Ia lahir di Kongo. Masa kanak-kanaknya yang indah berakhir karena sang ibu meninggal. Ia terpaksa dikirim ke kakak perempuannya di kota dekat Paris.
Kematian sang ibu yang ia panggil sebagai 'malaikat penyelamat' membuat masa kecilnya penuh depresi yang berlanjut hingga ia dewasa. Lubang menganga di hatinya tak bisa diobati meski dengan pernikahan bahagia dan menjadi seorang ibu.
Saat para pekerja sosial mencoba membantu keluarga imigran di Paris, Sophie memutuskan untuk menjadi mualaf, tanpa mengatakan apa pun kepada suaminya yang ateis. Ia berharap semoga kepercayaan barunya membawa kedamaian.
Dan benar, hatinya menjadi tenang. Namun, masalah lain muncul. Saat itu datang 3 pria muslim ke dalam hidupnya. Usia mereka 10 tahun lebih muda dan menjadikan dirinya kakak perempuan angkat.
Pada September 2014, ketiga pria itu menghilang. Rupanya mereka ke Suriah. Di kota itu, mereka menghubungi Sophie berkala. Mereka berkisah kepada Sophie bahwa ketiganya ke Suriah mencari ibunya yang hilang.
"Kisah mereka begitu mengharukanku karena aku merasa ada kemiripan antara mereka dan aku. Pelan-pelan mereka memainkan perasaanku. Mereka juga tahu bahwa aku adalah anak yatim piatu. Mereka tahu aku lemah," k Sophie lagi.
Pada 20 Februari 2015, Sophie pamit kepada sang suami bahwa ia akan bepergian, bekerja di sebuah panti asuhan di Istanbul untuk beberapa minggu dan membawa sang anak turut serta. Namun, itu adalah bualannya. Ia malah berangkat ke selatan Turki dan masuk ke Suriah.
Sophie menuju Raqqa yang ia kira adalah surga, seperti 3 pria itu ceritakan. Di sana, alih-alih mendapatkan taman firdaus, ia diwajibkan memakai burka, tidak diperbolehkan bepergian seorang diri, serta menyerahkan paspornya. Dan lebih pilu lagi, ia dibatasi tak boleh menghubungi keluarganya.
Di Raqqa, ia diharuskan bekerja di sebuah rumah sakit bersalin. Ia terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka memperlakukan pasien bukan berdasarkan tingkat gawat darurat, tapi berdasarkan status: militan ISIS atau bukan.
Butuh 10 hari bagi Sophie untuk sadar dengan apa yang terjadi. Apalagi kerap kali ia menerima surat-surat dari sang suami yang memintanya pulang.
"Aku minta kepada mereka untuk pulang. Tiap hari. Aku katakan kepada mereka aku rindu kepada keluargaku dan anakku butuh ayahnya. Awalnya mereka menolak halus, lama-lama mereka mengancamku. Mereka katakan aku adalah perempuan yang tinggal sendiri bersama anak, jadi aku tak boleh keluar. Kalau keluar, mereka akan rajam aku sampai mati," katanya.
Sang anak pun mulai gelisah dan rindu pulang.
"Aku takut kalau suatu hari mereka menahanku dalam penjara dan aku harus meninggalkan anakku bersama," ucap Sophie.
Di saat seperti itu, tiap malam Sophie selalu membisikkan kalimat indah dan positif di telinga sang anak.
"Tiap malam aku bisikkan bahwa ayahnya dan aku mencintainya, meminta mereka memperlakukan perempuan dengan baik. Itu aku lakukan tiap malam karena jika sampai suatu hari dia jatuh ke tangan mereka, yang ia ingat adalah suaraku.... Aku seperti singa betina yang melindungi anakku," ujarnya lagi.
Pada suatu hari, seorang pria Prancis memaksa anaknya untuk beribadah di masjid. Sophie menepis tangan si pria sambil berkata, "Lepaskan tanganmu dari anakku,"
Respons si pria? Sebuah tamparan telak di pipi Sophie.
"Aku ada di kota asing, tak kenal siapa pun, dan tak bisa berbahasa mereka. Saat kejadian itu, aku melihat ke anakku dan aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan fatal dalam hidupku. Aku pun memutuskan untuk jadi lebih kuat dan berjanji akan melakukan apa pun untuk keluar dari situ," kata Sophie.
Si pria itu lalu membawa Sophie dan anaknya ke madaffa, (guest house), sebuah nama samaran untuk penjara dan rumah bagi puluhan perempuan asing. Di situ Sophie kaget luar biasa melihat anak-anak kecil menonton rekaman ISIS memenggal tawanan sementara sang ibu bersorak dan bertepuk tangan.
"Para perempuan itu melihat 'pejuang' ISIS adalah 'pangeran tampan', orang yang kuat dan berpengaruh yang bakal melindungi mereka. Salah satu cara keluar dari madaffa adalah menikahi salah satu pejuang itu. Kenyataannya? Para perempuan Barat itu sekedar jadi mesin penghasil anak-anak ISIS."
Pada suatu hari, ketika penangkapnya mengurus pernikahannya, Sophie menemukan pintu tak terkunci. Ia kabur bersama sang anak. Ia terus berjalan, tanpa melihat ke belakang.
Sophie berhasil dari Raqqa. Di sebuah kota, ia ditampung oleh satu keluarga yang menanggung risiko karena telah menolongnya. Lalu Sophie menghubungi oposisi Suriah yang akhirnya memulangkan dirinya ke Prancis.
Pada suatu malam 24 April 2015, ia dibonceng pemuda Suriah naik motor. Memakai burka, ia menyembunyikan sang anak di dalamnya. Bertiga mereka berhasil menyeberang ke Turki. Ancaman jika tertangkap: mati.
Sesampainya di Paris, ia diinterograsi oleh pihak intelijen. Ia ditahan selama 2 bulan dan tak boleh melakukan kontak dengan keluarganya.
Hari Sabtu, 9 Januari 2016, ia dan suaminya telah bertemu. Namun Sophie masih bisa terancam pasal penculikan anak.
Bagaimana pun, perempuan 34 tahun itu sadar bahwa ia sangat beruntung bisa berhasil keluar hidup-hidup dari Suriah.
Sesaat setelah bertemu sang suami, ia menunjukkan foto anak mereka membawa senjata otomatis yang dikirim oleh salah satu anggota ISIS.
"Pasti diambil saat aku lengah. Sungguh menyakitkan. Aku akan selalu menyesal telah membawa putraku ke neraka. Sungguh ini neraka!" ujarnya penuh emosi.
"Aku tahu segala mimpi burukku telah berakhir. Kami masih hidup. Sekarang, aku punya kewajiban untuk mencegah mereka terbuai oleh ISIS. Please, jangan pergi (ke Suriah)...," kata Sophie menutup pembicaraan.**